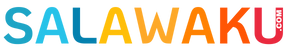Lemahnya Hukum dan Kesepakatan Damai Yang Dipaksakan
“Pada dasarnya hidup dalam himpitan ekonomi, ruang lingkup dan dinamika sosial yang terbatas semuanya dapat terjadi akibat konflik, sehingga tidak ada satupun manusia normal yang ingin hidup dalam konflik. Konflik hanya dianggap sebagai gagalnya negara dalam menegakan hukum dan lemahnya penegakan hukum secara maksimal”
Oleh Amirudin Latuconsina, SH, MH (Koordinator Komisi Yudisial Wilayah Maluku)
Ambon, SALAWAKU – Sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam kesatuan sistem Negara hukum, tentu diwajibkan untuk selalu taat hukum dalam dinamika kemasyarakatan. Ketaatan terhadap hukum di Maluku dalam kerukunan hidup orang basudara bukan hal baru.
Hal ini sudah terbentuk, bahkan sebelum negara Indonesia ini lahir. Hubungan pela dan gandong, ade dengan kaka, antara negeri beda agama maupun antara negeri tetangga sangat kental dan terikat oleh budaya dan adat istiadat. Hubungan ini kemudian dijadikan sebagai tradisi adat yang tidak bisa dinodai dan dingkari, sebab merupakan amanat leluhur yang dipercayai mengandung aspek religius magis.
Namun belakangan ini media cukup diramaikan konflik sosial di Maluku. Ada amanat penting dari Bapak Kapolda Maluku Drs. Lotharia Latif, SH. M.Hum, terkait 52 titik konflik yang tersebar di provinsi Maluku dan harus menjadi tanggungjawab bersama. Padahal jika dilihat dalam aspek hukum, maka salah satu sumber utama konflik sosial dan kekerasan diberbagai daerah akibat penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah.
Belum lagi ditambah dengan berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan marginalisasi. Pengaturan sosial ekonomi yang tidak tepat sasaran, politik kepentingan dan pemanfaatan sumber daya alam jauh dari asas keadilan, bahkan dalam kehidupan berbudaya. Klimaksnya munculah berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat umum, berkecamuk dan meledak menjadi konflik sosial dan tragedi kemanusiaan yang sangat bertentangan dengan konsep Negara hukum.

Pola penerapan hukum dan lemahnya penegakan hukum secara adil di republik ini telah menjadi embrio timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia.
Fase otoritarian selama empat dasawarsa sejak masa orde lama hingga dan orde baru, telah melahirkan sistem hukum represif yang secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku dan struktur sosial yang menjadikan kekerasan sebagai norma utama.
Sedangkan reformasi hanya dianggap sebagai kamuflase dari orde lama dan orde baru yang tidak mampu merealisasikan penerapan hukum dari represif menjadi hukum responsif.
Pada dasarnya hidup dalam himpitan ekonomi, ruang lingkup dan dinamika sosial yang terbatas semuanya dapat terjadi akibat konflik, sehingga tidak ada satupun manusia normal yang ingin hidup dalam konflik. Konflik hanya dianggap sebagai gagalnya negara dalam menegakan hukum dan lemahnya penegakan hukum secara maksimal. 52 titik konflik yang disampaikan oleh Kapolda hanya terkait persoalan tapal batas wilayah.
Sedangkan narasi 52 titik konflik ini bukan hal baru, hal ini sdah sering kita dengar sejak beberapa tahun yang lalu, Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar konflik yang terjadi di Maluku dapat diakibatkan oleh ketidakpekanya negara dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Konflik di pulau haruku antara negeri Pelauw dengan Negeri Kariu adalah salah satu akibat dari lambat dan ketidakpekanya Negara dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memilih memproduksi kekerasan melainkan melihat bentuk dan produksi hukum di republik ini, bahkan kekerasan sudah dianggap sebagai metode paling jitu dalam menyelesaikan persoalan. Jika demikian, buat apa kita bernegera?
Sebelum konflik antara Negeri Pelauw dan Negeri Kariu pecah, masyarakat pelauw melalu organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Matasiri (IPPMAP) telah meminta pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Kapolda, Pangdam dan Gubernur) guna membahas situasi kambtibmas antara kedua Negeri tersebut sejak September 2021. Namun hal ini tak direspond oleh Pemerintah Daerah sehingga klimaksnya, konflik terjadi di tanggal 26 Januari 2022.
Tentunya ini adalah fakta gagal dan lambatnya Negara dalam merespond dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Konflik yang terjadi antara Negeri Pelauw dan Negeri Kariu adalah akibat gagalnya negera.
Setelah konflik terjadi, dan telah merenggut tiga nyawa masyarakat Negeri Pelauw yang meninggal akibat konflik, sekitar 6000 pohon cengkih dan pala yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pelauw sejak dulu kala di tebang, kini Negara mulai hadir dengan skema penyelesaian konflik dan terkesan memaksakan kedua negeri hidup damai.
Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Negara melalui pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dianggap sebagai langkah yang keliru karena dilakukan secara tergesa-gesa, memaksa dan tidak memperhatikan amanat UU tersebut.
Penanganan Konflik
Jika merujuk Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup tiga aspek utama yakni, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
Pertama, Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pada point ini, Negara telah gagal dalam melakukan pencegahan konflik.
Hal ini terbukti dengan Negara (Pemerintah daerah) tidak peka dalam merespond pertemuan pada bulan September 2021 dengan masyarakat pelauw guna membahas situasi kemanan kedua Negeri.
Kedua, Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Negara tidak belum maksimal dalam upaya melakukan pemulihan pasca konflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi.
Rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi telah diuraikan didalam pasal 37, 38 dan 39 UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial. Rekonsiliasi mengandung tiga point penting yang harus diselesaikan oleh Negara yakni, perundingan secara damai, pembayaran restitusi dan pemaafan.
Ketiga hal ini belum terealisasi selama proses penangan konflik Pelauw dan Kariu hingga saat ini. Pertama, belum pernah ada perundingan secara damai oleh kedua negeri kecuali jika dipaksakan oleh Negara.
Kedua, belum ada pergantian restitusi oleh Negara terkait kerugian akibat konflik. Ketiga, belum ada kata saling memaafkan yang lahir atas keasadaran sendiri dari kedua negeri yang bertikai.
Sedangkan untuk rehabilitasi berdasarkan amanat pasal 38. Pertama, terdapat aspek pemulihan psikologi korban yang belum terlaksana. Kedua, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban dan Ketiga pemulihan ekonomi dan hak keperdataan.
Amanat di dalam UU merupakan tuntutan yang telah disampaiakan oleh Negeri pelauw ke Negara melalui berbagai pertemuan, baik dengan Kepolisian, TNI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Maluku tengah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Menkopolhukam, Komnas HAM dan terakhir dengan KSP.
Dari sekian banyak pertemuan ini, negeri pelauw menuntut banyak hal termasuk ganti rugi atas penebangan 6000 lebih pohon cengkih dan pala yang menjadi sumber kehiudpan masyarakat pelauw, tuntutan terhadap warga kariu untuk meminta maaf secara terbuka melalui media kepada masyarakat pelauw atas pengrusakan situs keramat negeri pelauw, tuntutan pemulihan psikologi, pemulihan ekonomi dan hak keperdatan yang hingga saat ini belum ada satupun tuntutan dipenuhi oleh Negara.
Padahal amanat Undang-undang ini jelas bahwa dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan.
Sedangkan tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan.
Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
Hal ini tentunya menjadi point penting yang harus dilaksanakan oleh Negara dalam penanganan konflik sosial. Negara diharuskan bersikap profesional dalam menentukan kebijakan dengan melihat akar persoalan konflik.
Tentunya sebagai warga Negara yang baik, kita wajib patuh terhadap kebijakan Negara. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan kebijakan terkait penangan konflik sosial, Negara harus menyelesaikan dulu persoalan dasar yang menjadi cikal bakal lahirnya konflik di masyarakat.
Rekonsiliasi dan penandatangan kesepakatan damai antara Negeri Pelauw dengan Negeri Kariu yang dimediasi oleh Pemerinatah daerah pada senin, 14 November 2022 kemarin merupakan cara-cara Negara yang memaksakan kehendak masyarakat untuk hidup damai, berdampingan tanpa mengobati luka yang belum sembuh.
Harusnya membangun pola hidup yang damai harus berawal dari mengatur pola pikir, cara bersikap, perilaku, karakter dan watak masyarakat, menyelesaikan persoalan psikologi masyarakat akibat konflik, membentuk mentalitas untuk siap hidup berdampingan juga dengan membangun tata kehidupan bersama bedasarkan nilai-nilai luhur beasaskan keadilan, kesetaraan dan demokrasi.
Hal ini dapat dilakukan, melalui metode penyelesaikan akar permasalahan konflik yang terjadi di level masyarakat bawah (basis struktur), sedangkan pertemuan kemarin hanya melibatkan kelas menengah keatas (supra struktur). Sehingga masyarakat Negeri Pelauw (basis struktur) berani mengambil sikap untuk tetap menolak berdamai dengan kariu jika semua tuntutan yang menjadi akar persoalan konflik dan akibat konflik belum direalisasikan oleh Negara.
Metode penanganan konflik sosial harus menyentuh ke dasar persoalan. Persoalan dasar konflik antara negeri Pelauw dan Negeri Kariu yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh negara, yakni persoalan hak ulayat, persoalan keramat ua rual, persoalan tapal batas, dan persoalan pemulihan ekonomi serta ganti rugi. Hal ini harus terselesaikan lebih dulu, sehingga dapat menjadi presenden yang baik bagi pihak-pihak yang berkonflik.
Sebab, jika Negara memaksa kehendak, dengan kebijakan memulangkan negeri Kariu ke tempatnya untuk hidup damai berdampingan dengan negeri Pelauw tanpa menyelesaikan segala tuntutan yang menjadi dasar konflik, maka ini adalah damai yang dipaksakan dan tentunya berpotensi melahirkan konflik baru. Damai harus benar-benar dirasakan serta lahir dari kedua Negeri yang bertikai. (*)